Dilema Pendidikan Karakter
PENDIDIKAN kita sedang dihimpit dilema, antara mengutam`kan pembentukan karakter siswa atau memenuhi kepentingan tes. Di satu sisi, diharapkan akan lahir anak-anak didik yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter atau kepribadian yang baik. Tujuannya agar lahir generasi yang berkembang dengan karakter berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa dan agama (UU Sisdiknas 2003; Suyanto, 2009). Sedangkan di sisi lain, diharapkan semua siswa mampu menjawab soal tes, terserah bagaimana caranya.
Para peneliti menemukan bahwa pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa ada role model atau orang yang patut diteladani. Pertanyaan, siapa yang layak dijadikan role model untuk dijadikan contoh oleh para siswa sebagai hasil pendidikan yang baik saat ini?
Setidaknya, guru-guru yang memenuhi syaratlah yang menjadi role model utama bagi siswa (Lumpkin, 2008). Mereka punya kesempatan untuk membentuk karakter siswa, misalnya, dengan melaksanakan saling menghargai dan bertanggungjawab dalam proses pembelajaran (Lickona, 1991). Namun, guru-guru pun dalam pembelajaran dan kesehariannya harus mengejar kurikulum dan berorientasi kepada tes ketimbang pengembangan karakter siswa. Hasilnya, pendidikan kebut hasil tes, yang dalam bahasa Aceh saya gunakan istilah ‘karattes’ atau kebut belajar untuk tes.
Mengutamakan hasil tes
Pendidikan yang lebih mengutamakan hasil tes akan cenderung mengabaikan prosesnya. Sedangkan pendidikan karakter memerlukan penglibatan proses pengembangan kognitif sekaligus sosial siswa. Lebih-lebih, pengetahuan umumnya dikonstruksi bersama dengan cara berinteraksi dengan para siswa lain dan atau guru. Pendidikan seperti ini akan membantu melahirkan siswa yang menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapatnya, mampu bekerja dalam tim, dan mengutamakan kemampuan pengambilan keputusan secara bersama-sama.
Karena belajar sifatnya interaktif, bahasa merupakan alat yang sangat besar perannya. Penggunaan bahasa-bahasa yang sifatnya mengajak, bahasa menghargai pendapat orang lain, bahasa yang mengandung harapan kemajuan, dan sejenisnya. Namun, yang dikhawatirkan kalau ada guru atau dosen yang karena merasa ilmunya hebat, dengan angkuh menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya mengejek, menjatuhkan martabat, dan sejenisnya. Ini bisa dikatakan sebagai oknum yang cacat karakter baik dalam berbahasa. Padahal sebagian karakter manusia ditunjukkan lewat bahasa yang digunakannya.
Cacat dari segi karakter, disengaja atau tidak, bisa juga terjadi dalam dunia pendidikan secara hirarkis. Misalnya, kalau sekolah-sekolah dalam suatu kecamatan banyak yang tidak lulus ujian nasional, maka kepala sekolahnya akan diberikan sanksi tertentu. Lantas kepala sekolah pun menggunakan bahasa-bahasa ancaman kepada guru-gurunya. Mulailah para guru bergerilya mempersiapkan siswa-siswanya dengan soal-soal ujian yang begitu banyak. Dan ada juga yang membantu siswa menjawab soal ketika ujian. Inilah yang terjadi bila pendidikan lebih mengutamakan pada hasil tes.
Pelajaran buruk
Dilihat dari perspekstif pendidikan karakter, proses seperti itu malah mendegradasi karakter guru dan menjadi pelajaran buruk bagi pembentukan karakter siswa. Pada kasus memberikan kunci jawaban kepada murid-muridnya, guru telah mengorbankan idealismenya demi hasil tes. Kebenaran telah tergantikan dengan pembenaran (yang salah). Disadari atau tidak, ini adalah praktek yang merusak nilai pendidikan dan menghancurkan pilar-pilar pembentuk karakter siswa. Karakter kejujuran menjadi terkorbankan demi hasil berbentuk angka-angka tinggi.
Bila hal ini terpelihara dalam sistem pendidikan kita, para penyelenggara pendidikan akan menjadi bagaikan robot. Sebagaimana lazimnya, robot hanya menjalankan tugas-tugas yang sudah diprogramkan dalam mesinnya, tanpa melibatkan unsur-unsur psikologis, tanpa mampu memikirkan nilai-nilai kemanusiaan, perbedaan kepentingan manusia, atau potensi yang berbeda yang dimiliki masing-masing siswa, dan lain-lain.
Pendidikan seperti ini tak terlepas dari faktor kultural dan historis yang diterima secara pasif, yang hanya membentuk anak untuk menerima saja secara pasif, tanpa mempertanyakan mengapa demikian. Budaya seperti ini biasanya terjadi pada orang-orang yang pernah dijajah, yang harus tunduk kepada pihak penjajah, agarnya hegemoninya terus berlangsung. Budaya seperti ini kadangkala dibawa ke dalam kelas belajar, apalagi kelas merupakan wilayah produksi dan reproduksi budaya.
Budaya seperti ini pada saatnya akan melahirkan masyarakat yang pasif. Lihatlah bagaimana rakyat terus dirundung kemiskinan, tetapi tidak gencar mempertanyakan mengapa terus miskin. Padahal kemiskinan tidak bisa hanya dilihat secara mikro (pada orang miskin saja), tetapi penting melihat secara makro (pada institusi negara dan bahkan agenda global). Bisa saja mencurigai kemiskinan tak luput dari agenda politik global.
Apalagi akan sangat terbuka kesempatan menguasai dunia bila terdapat banyak orang miskin dan kurang ilmu pengetahuan. Sebagaimana diketahui, kapitalis menguasai sumber-sumber dunia lewat privatisasi dan liberalisasi. Hanya sebagian orang saja, terutama orang-orang yang terlibat dalam negosiasi, yang beruntung, sedangkan rakyat jelata akan terus buntung.
Proyek ‘cilet-cilet’
Padahal di sejumlah negara (seperti Arab Saudi) terbukti, nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar yang mengeruk kekayaan alam di negerinya merupakan solusi mujarab untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, mengapa ini tidak dijalankan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, termasuk di Aceh? Mengapa pengentasan kemiskinan penduduk yang begitu besar persentasenya hanya dijalankan dengan proyek cilet-cilet dan dengan dana kecil? Dan, mengapa masyarakat banyak diam tidak mempertanyakannya? Tidak tertutup kemungkinan keadaan masyarakat seperti ini lahir dari rahim pendidikan pasif.
Dalam politik lokal pun, banyaknya orang miskin dan kurang pengetahuan merupakan suatu peluang. Dengan sedikit “pemberian” saja, banyak orang miskin akan mengorbankan idealismenya untuk memilih orang-orang tertentu, meskipun tidak punya kapasitas, dalam Pilkada, misalnya. Padahal memilih orang-orang yang kurang mampu atau terlalu berorientasi bisnis bisa menambah lama masa dan parah kemiskinan masyarakat, karena yang dipilih lebih beriorientasi memperkaya diri ketimbang memakmurkan rakyatnya dan merusak tatanan pemerintahan. Apalagi sudah lazim terjadi, orang yang sudah banyak mengeluarkan modalnya, akan lebih mengutamakan upaya untuk pengembalian modalnya berkali lipat.


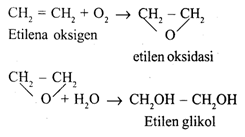

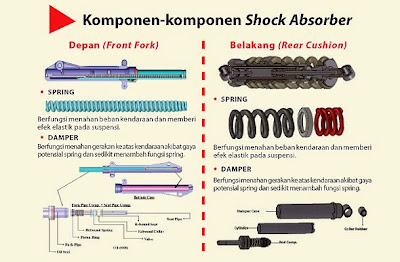
Komentar